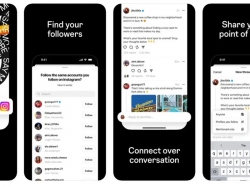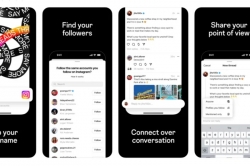Kasus Lukas vs BRI, dan kita yang suka dengan berita sampah
Hoaks di media sosial lebih cepat menyebar daripada berita benar, dan manusialah yang patut disalahkan, bukan robot.
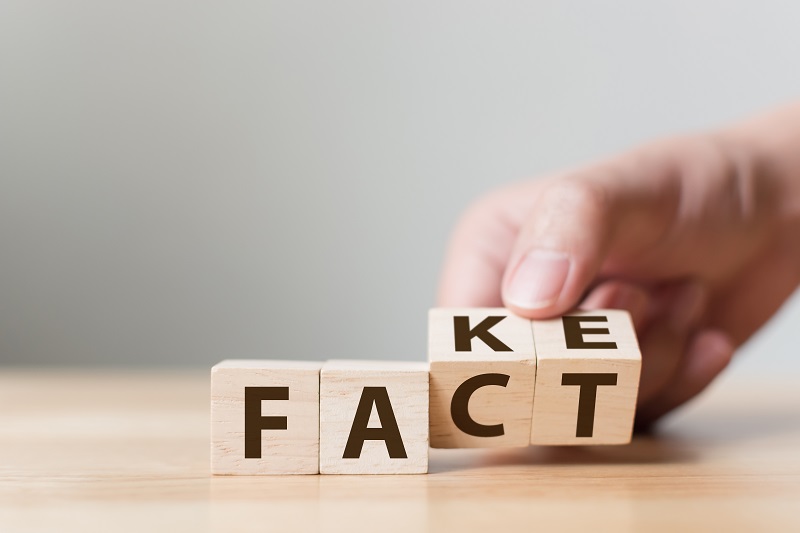
Human vs bot dan kecepatan hoaks
Status dari akun-akun yang ikut mengamplifikasi misinformasi ini menunjukkan cluster data yang menarik. Sebanyak 73,8 persen merupakan akun biasa. Sementara itu, hanya 26,2 persen saja yang berupa akun bot.
Berdasarkan hasil penelitian Sinan dan rekan-rekan dari MIT Media Lab, tweet yang bercerita fakta hanya menggapai reach tak lebih dari seribu pemirsa Twitter. Sementara itu, informasi hoaks mampu menggapai seribu sampai seratus ribu pengguna Twitter. Isu-isu politik pun tergolong masuk dalam kategori yang cepat viral di Twitter.
Berita sampah di medsos
Kasus Lukas ini pun tak lebih dari berita sampah (Junk News) yang teramplifikasi media sosial dan media online. Media online tidak melakukan tugasnya untuk verifikasi. Media online hanya mementingkan jumlah klik di Google Analytics mereka. Tidak mengherankan, banyak konten berkualitas rendah dan clickbait mudah sekali kita temui di media sosial.
Menurut penelitian Samantha Bradshaw, kandidat PhD dari Oxford Internet Institute yang membuat penelitian soal Proyek Propaganda Komputasional, ada tiga alasan kuat kita terjebak konten sampah di medsos.
Pertama, algoritma pencarian di media sosial menjadi biang keladinya. Tanpa algoritma ini, kita tidak mungkin mampu memilah informasi di media sosial yang sangat masif. Akan tetapi faktanya, algoritma tersebut memprioritaskan konten-konten tertentu. Algoritma Facebook, misalnya, memprioritaskan konten dengan engagement yang tinggi agar memperoleh paparan tinggi di platform mereka.
Ini artinya, makin banyak like, komentar, dan share, maka makin viral konten tersebut. Tidak peduli isi beritanya rendah ataupun hoaks. Algoritma yang sama pun berlaku di platform seperti YouTube. Hal ini pula yang dimanfaatkan politikus untuk propaganda politik.
Pada dasarnya, algoritma Facebook, Google, dan Twitter dirancang untuk menyeleksi dan memprioritaskan topik maupun konten tertentu yang membangkitkan keterikatan emosional dengan pengguna (engagement). Algoritma ini menciptakan gelembung filter yang membatasi penyebaran informasi penting lainnya di jejaring media sosial.
Dengan kata lain, sekali Anda terpapar konten A, maka algoritma akan merekamnya sebagai personalisasi diri Anda. Jadi tidak aneh, Anda akan menerima konten serupa setelah itu. Inilah cikal bakal efek viral di internet. Kita, memusatkan diri pada informasi yang tampaknya diikuti banyak orang di media sosial.
Di Indonesia, kemunculan bintang YouTube kontroversial seperti Young Lex dan Awkarin merupakan buah dari filterisasi algoritma media sosial ini. Tidak peduli keduanya menerima komentar pedas maupun jutaan dislike dari warganet, namun kenyataanya mereka meroket menjadi fenomena media sosial dalam tempo singkat.
Jadi, meski kesempatan mengakses informasi di internet sangat terbuka, algoritma membuat kita sulit menemukan informasi yang kritis dan menawarkan sudut pandang lain dari sebuah topik.
Alasan kedua kenapa berita sampah makin banyak kita temukan di media sosial adalah iklan. Memanfaatkan karakter clickbait dan data pengguna yang dihimpun platform media sosial, iklan di media sosial jadi memiliki kekuatan untuk menargetkan pengguna secara presisi.
Dalam praktiknya, cara efektif untuk mendulang engagement adalah dengan menyinggung eksistensi dan jati diri pengguna agar tergugah. Hal ini makin menggelembungkan informasi kurang akurat, dan konten-konten bernada polarisasi di internet. Ini makin menambah daftar timbunan berita sampah di media sosial.
Kampanye politik dan operasi dari luar negeri menggunakan media sosial untuk mengiklankan konten strategis dan manipulatif buatan mereka dengan cara-cara seperti ini.
Ketiga, alasan kenapa makin banyak berita sampah di media sosial adalah eksposur atau paparan konten yang dipilih pengguna sendiri. Pengguna media sosial sendirilah yang memfilter informasi yang mereka sukai dan tidak suka. Sebenarnya ini bumerang bagi pengguna. Pasalnya, paparan informasi yang pengguna dapatkan jadi tidak beragam. Gampangnya begini, kalian meng-unfollow semua orang yang kalian tidak setujui pendapatnya di Facebook. Hal semacam ini sangat lumrah terjadi saat kasus Ahok.
Studi akademik mendemonstrasikan bahwa orang-orang cenderung membagikan informasi yang mereka “yakini” sebelumnya, ke jejaring sosial mereka. Ini memperdalam perbedaan ideologi antara mereka dengan kelompok pengguna media sosial lainnya. Hasilnya, informasi dan pengetahuan yang mereka dapatkan tidak berimbang dan cenderung mempertajam satu sudut pandang saja.
Tidak aneh, pada akhirnya makin ke sini, pengguna media sosial makin partisan. Yang tidak ikut politik, misalnya, sibuk apatis dengan dunia mereka sendiri. Hal ini karena kita cenderung menyeleksi paparan yang kita terima dan susah menerima informasi baru yang sangat jauh dan terasa radikal.
Berkaca dari kasus Lukas, isu-isu hoaks di media sosial tidak bisa lagi kita anggap enteng. Terbukti, berawal dari misinformasi secuil di media sosial, mampu mengguncangkan perusahaan sekelas BRI.
Fenomena lainnya, media online pun kini makin mudah memuat berita berdasarkan status viral di media sosial. Meski pada akhirnya ada klarifikasi, namun tetap saja peran media sosial dan media online sebagai penggiring opini masih kuat.
Ada satu pelajaran dari kasus Lukas dan penelitian tentang hoaks dari tim MIT Media Lab ini. Tidak ada filter yang lebih tangguh menangkal hoaks di media sosial kecuali pengguna media sosial itu sendiri. Jadi, hati-hatilah untuk mengklik tombol share di medsos! Siapa tahu hoaks berikutnya berawal dari satu klik yang kamu mulai. Viralkan!