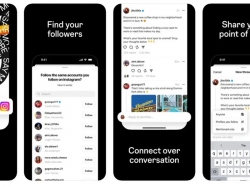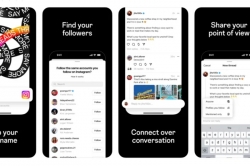Mempersenjatai media sosial: dari Rusia sampai MCA
Angkatan kelima -wacana mempersenjatai buruh dan tani di era 65- terwujud dalam bentuk lain di era media sosial. Bagaimana seluk beluknya?

You're not real. And what? You are? Is any of it real? I mean, look at this! Look at it! A world built on fantasy. Synthetic emotions in the form of pills. Psychological warfare in the form of advertising. Mind-altering chemicals in the form of food. Brain-washing seminars in the form of media. Controlled isolated bubbles in the form of social networks. -Mr.Robot
Dunia memang tak semuram pandangan Mr.Robot yang mengibaratkannya sebagai Controlled isolated bubbles in the form of social networks. Tapi kita tak bisa membantah fakta bahwa jejaring sosial telah membuat jutaan orang hidup dalam gelembung-gelembung unik ciptaan algoritma komputer.
Salah dua dari gelembung itu sudah akrab kita lihat di media sosial: dari bani taplak sampai cebongers. Apa yang sekilas terlihat lucu-lucuan ini sebenarnya berbahaya bagi masyarakat dalam konteks lebih luas. Orang atau sekelompok orang bisa mempersenjatai media sosial untuk tujuan tertentu, baik ekonomi maupun politik. Imbasnya tak bisa diremehkan. Perbedaan pandangan kian meruncing dan bisa mengarah kepada konflik terbuka.
Amerika Serikat sudah memetik pelajaran berharga bagaimana media sosial dipersenjatai Rusia untuk mengintervensi pemilihan presiden di negara tersebut pada 2016 lalu. Di Tanah Air, kita punya kasus Saracen dan Muslim Cyber Army (MCA).
Bagaimana kelompok kriminal mempersenjatai media sosial?
Media sosial bisa digunakan dengan gratis. Lalu, darimana Facebook mendapatkan penghasilan puluhan miliar dalam satu tahun? Iklan. Berbeda dengan iklan di televisi, memasang iklan di media sosial memungkinkan pengiklan untuk menargetkan sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu, seperti gender, lokasi, umur, dan juga ketertarikan yang diukur dengan parameter sangat spesifik.
Targeted advertising atau iklan tertarget tidak hanya bisa digunakan oleh perusahaan, tapi juga pemerintahan sebuah negara untuk memengaruhi warga dari negara lain. Rusia memengaruhi pemikiran warga Amerika Serikat dalam pemilihan presiden pada 2016 lalu.
Menurut CNN, Facebook memperkirakan sekitar 10 juta orang di Amerika Serikat melihat setidaknya 3.000 iklan politik yang dibuat akun-akun terkait dengan pemerintah Rusia selama Pemilu 2016. Para ahli percaya, perkiraan Facebook ini jauh lebih rendah dari angka sebenarnya. Perkiraan paling banyak, ada 70 juta orang yang melihat iklan-iklan tersebut dan memengaruhi pemikiran mereka ketika mereka memberikan suara mereka.
Selain Facebook, Rusia juga memanfaatkan Google dan Twitter. Data Business Insider menyebutkan, mereka menghabiskan USD60 ribu untuk beriklan di Google, USD100 ribu di Facebook dan USD270 ribu di Twitter. Jumlah tersebut sebenarnya tak besar jika dibandingkan dengan total biaya kampanye Donald Trump dan Hillary Clinton. Masing-masing kandidat menghabiskan hampir USD1,9 juta.
Rusia tidak hanya mengandalkan iklan tertarget pada media sosial. Mereka juga membuat persona online untuk memengaruhi masyarakat AS. Menurut pengacara AS, Robert Mueller, Rusia telah menghabiskan puluhan juta dollar dalam waktu beberapa tahun untuk mengembangkan sistem dengan tujuan memengaruhi pendapat masyarakat AS.
Seperti disampaikan Wired, Rusia membangun identitas online yang terlihat otentik, baik akun perseorangan atau grup. Untuk membuat persona buatan tersebut semakin meyakinkan, Rusia bahkan menggunakan server dan VPN yang ada di AS. Dengan begitu, persona palsu buatan mereka samaran itu bisa terlihat seolah-olah memang tinggal di AS.
Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga menggunakan ID AS yang tercuri -- seperti SIM -- untuk menguatkan identitas online tersebut. Identitas-identitas online itu juga digunakan untuk melakukan pembayaran via PayPal dan akun cryptocurrency.
Tujuannya, untuk membuat mereka terlihat seperti orang AS asli dan menyuarakan kekhawatiran warga AS. Williams dan Kalvin adalah dua contoh blogger palsu buatan Rusia. Berpura-pura sebagai warga AS keturunan Afrika, mereka membuat konten untuk mendiskreditkan Clinton, pesaing Trump dalam pemilu 2016.
Keduanya memiliki akun di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube.
"Konten Williams dan Kalvin dihapuskan dari Facebook pada Agustus setelah diketahui bahwa keduanya adalah akun propaganda Rusia," tulis Daily Beast.
Rusia juga membuat grup bernama United Muslims of America, yang membuat konten berupa meme yang menunjukkan bahwa Hillary Clinton mengakui bahwa AS "menciptakan, mendanai dan mempersenjatai" al-Qaeda dan juga ISIS. Pada saat yang sama, Rusia juga berusaha untuk membuat warga Muslim di AS resah dengan mendukung orang-orang anti-Muslim.
Pada dasarnya, tujuan Rusia hanya satu: kacaukan AS. Mereka melakukan ini dengan membuat warga AS bertengkar dengan satu sama lain dan memulai konflik. Strategi utama mereka? Membantu Trump -- yang salah satu senator dari partainya sendiri akui tidak pantas menjabat sebagai presiden -- menjadi presiden.
Metode yang digunakan Rusia, menurut Mueller, adalah meniru grup "radikal". Konten yang mereka buat tidak bertujuan untuk mengubah pandangan audiens mereka, tapi untuk memperkuat kepercayaan tersebut dengan cara "mengonfirmasi" pandangan yang seseorang telah miliki. Fenomena inilah yang jamak disebut sebagai bubble. Dengan begitu, orang itu akan mengubah tingkah lakunya, tapi tidak pandangannya.
Menurut Mueller, konten yang Rusia buat tidak hanya iklan berbayar, tapi iklan natif, berupa video, gambar, meme dan juga teks dengan tujuan untuk menjatuhkan karakter lawan -- dalam hal ini Clinton -- dan membuat masyarakat berpikir akan adanya konspirasi. Semua konten ini dibuat sedemikian rupa untuk membuatnya terlihat seperti konten asli buatan warga AS.
Konten yang mereka buat tidak bertujuan untuk mengubah pandangan audiens mereka, tapi untuk memperkuat kepercayaan tersebut dengan cara "mengonfirmasi" pandangan yang seseorang telah miliki. Fenomena inilah yang jamak disebut sebagai bubble.
Konten buatan Rusia beragam, mulai dari gambar Bernie Sanders dengan pose superhero yang mendukung hak-hak kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) sampai gambar Yesus yang beradu panco dengan Iblis.
II. Saracen dan Muslim Cyber Army di Indonesia
Sekarang, apa yang terjadi di AS pada 2016 tengah terjadi di Indonesia. Hanya saja, bukan pemerintahan negara lain yang memanfaatkan media sosial untuk memengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri.
Alasannya? politik dan ekonomi. Pihak yang menyebarkan konten untuk menggiring opini masyarakat akan mendapatkan untung dari pihak yang berkepentingan. Konten ujaran kebencian berbau SARA (Suku, Ras, Agama dan Antargolongan) menjadi bisnis baru. Hal ini terbukti dengan keberadaan Saracen, yang ditangkap pada tahun lalu.

Pada bulan Agustus lalu, Kasubdit 1 Dit Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Irwan Anwar di Gedung Divisi Humas Polri mengatakan bahwa kelompok Saracen memanfaatkan lebih dari 2.000 akun media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian.
Namun, seperti yang dikutip dari Tempo, dalam rilis resmi, kepolisian mengatakan bahwa jaringan Saracen memiliki lebih dari 800 ribu akun media sosial. Menariknya, jaringan Saracen melakukan operasi secara teroganisir. Kabag Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Awi Setiyono, menjelaskan, Saracen memiliki grup wilayah. Itu menunjukkan bahwa usaha penyebaran konten kebencian tidak dilakukan oleh perseorangan.
Sama seperti usaha lainnya, Saracen memiliki klien. Dan “pembeli” itulah yang akan menentukan konten yang Saracen buat. Menurut penulusuran polisi terhadap salah satu anggota, Sri Rahayu Ningsih, banyak konten buatan Saracen yang berisi kritik pada pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo.
Belum satu tahun sejak Saracen tertangkap, polisi kembali mengungkap jaringan Muslim Cyber Army. Keberadaan MCA diketahui pertama kali ketika Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri menangkap sejumlah tersangka penyebaran hoaks dan menemukan bahwa orang-orang itu tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang bernama Muslim Cyber Army.
Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa MCA memiliki akademi tempur dan sniper. Tim dari akademi tersebut bertugas untuk membuat isu provokatif dan menyebarkannya melalui media sosial.
Beberapa contoh isu yang diangkat antara lain kebangkitan PKI dan penculikan ulama. Sebagai pelengkap, tim itu juga bertugas untuk membuat konten ujaran kebencian pada sejumlah tokoh di pemerintahan.
Pada akhir Februari lalu, Polri telah berhasil menangkap anggota MCA yang tersebar di lima kota yang berbeda. Kelima kota itu adalah Jakarta, Pangkal Pinang, Bali, Sumedang, Palu dan Yogyakarta. Polri juga menemukan bahwa ada pelaku yang berada di luar Indonesia, seperti Korea Selatan.
Salah satu anggota dari The Family MCA bernama Tara Arsih Wijayani. Seorang dosen di UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta itu memiliki peran untuk menyebarkan konten ujaran kebencian.
Tersangka anggota The Family MCA lainnya memiliki inisial ER. Dia dulunya bekerja sebagai guru. Dia merupakan bagian dari berbagai grup di media sosial, seperti Muslim Cyber Admin (MCA), Republik Muslim Cyber Army, MCA news region, dan grup spirit 212.
Untuk saling berkomunikasi, anggota The Family MCA mengunakan Telegram dan Facebook selain aplikasi Zello. Sebagai bagian dari pemberantasan jaringan MCA, polisi bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi aplikasi tersebut.
III. Tahun politik, pertempuran mulai dari media sosial
Penangkapan anggota Saracen dan MCA bukanlah berarti tanda berakhirnya propaganda, misinformasi, dan hoaks di media sosial. Tahun ini hingga tahun depan, Indonesia akan menghelat pemilu akbar untuk memilih kepala daerah, legislator, dan presiden. Pertempuran opini akan dimulai dari media sosial untuk menjatuhkan lawan dan mengunggulkan jagoan.
Facebook, salah satu area utama penyebaran hoaks bukannya tak menyadari hal ini. Di beberapa negara, mereka aktif bekerja sama dengan otoritas setempat untuk mencegah penggunaan Facebook sebagai senjata mempengaruhi pemilihan umum. Di antaranya di Jerman dan Prancis.
Dalam skala yang lebih besar, Facebook berbenah dengan mengubah algoritma yang mengatur News Feed atau Kabar Berita di laman mereka.
Tudingan bahwa Facebook bisa mempengaruhi hasil pemilu suatu negara pada awalnya berawal di Pilpres Amerika Serikat yang dimenangkan Donald Trump. Pada awalnya, CEO Facebook Mark Zuckerberg menganggap tudingan itu sebagai hal yang gila. Namun belakangan dia menyadari bahwa dia salah.
Zuckerberg kemudian melakukan beberapa perubahan pada Facebook dengan tujuan untuk mempersulit penyebaran hoaks dan berita palsu. Salah satunya dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai fact checker atau pemeriksa fakta.
Cara lain yang Facebook gunakan adalah dengan memberikan tanda pada berita yang telah terbukti salah. Tanda yang dinamai Disputed Flag ini diluncurkan pada Desember tahun lalu. Sayangnya, cara tersebut ternyata tidak efektif. Karena itulah, Facebook mencoba untuk mencari cara lain.
Menurut laporan The Verge, cara baru yang Facebook gunakan adalah Related Articles yang berfungsi untuk memberikan konteks pada berita bohong yang seseorang baca dan hendak bagikan. Facebook juga menyebutkan, Related Articles dapat mempercepat proses dalam melawan hoaks.

"Menggunakan bahasa yang tidak terkesan menghakimi membantu kami untuk mengembangkan produk yang memungkinkan kami untuk berkomunikasi dengan orang-orang dengan sudut pandang beragam," kata Facebook ketika itu.
Pada awal tahun ini, Zuckerberg juga mengumumkan keputusan Facebook untuk mengubah algoritmanya sehinga Anda akan lebih sering melihat konten buatan teman dan keluarga Anda di beranda dan bukannya konten penerbit atau media. Zuckerberg ingin, pengguna menghabiskan waktu lebih sedikit di Facebook, tapi waktu tersebut adalah waktu berkualitas.
Namun, hal membuat pembuat konten dan media menjerit. Bahkan, ada penerbit yang sampai harus tutup.
Facebook mengubah algoritmanya sehinga Anda akan lebih sering melihat konten buatan teman dan keluarga Anda di beranda dan bukannya konten penerbit atau media.
Ialah LittleThings, penerbit konten yang fokus pada konten wanita. Sejak diluncurkan pada 2014, LittleThings telah mendapatkan lebih dari 12 juta pengikut di Facebook. Biasanya, menurut Business Insider, video yang diunggah penerbit ini bisa mendapatkan ribuan atau bahkan jutaan view.
Sayangnya, karena keputusan Facebook mengubah algoritmanya, LittleThings kehilangan 75 persen trafik organiknya, yang pada akhirnya berujung pada berkurangnya keuntungan yang mereka dapat.
Sama seperti Facebook, Twitter juga dipenuhi dengan berita palsu dan misinformasi. Studi MIT belum lama ini menunjukkan bahwa "kebohongan" menyebar dengan lebih cepat daripada kebenaran. Pada pertengahan tahun lalu, Twitter sempat dikabarkan tengah mengembangkan fitur laporan yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan informasi yang salah.
Pada pertengahan Februari 2018, Twitter kemudian mencoba untuk menyiarkan berita dari TV lokal saat muncul berita buruk seperti bencana, baik bencana alam atau bencana yang disebabkan manusia.
Berdampingan dengan video dari TV lokal, Twitter akan menampilkan kicauan yang membahas kejadian tersebut di beranda penguna. Tujuannya adalah untuk memberikan konten yang kredibel juga relevan pada pengguna.
Sementara Google melawan berita palsu dengan memberikan tool bagi pengguna untuk melaporkan konten yang dianggap tidak pantas atau berisi informasi salah. Selain itu, perusahaan pencarian tersebut juga berjanji untuk memperbaiki algoritma mereka agar hasil pencarian yang ditampilkan menjadi lebih relevan.
Google juga memperbaiki mesin pencari untuk "menampilkan halaman yang lebih bisa dipercaya dan menurunkan ranking konten kualitas rendah", seperti yang dikutip dari The Guardian. Namun, keputusan Google ini dianggap terlalu tidak jelas, menurut ahli mesin pencari dari perusahaan konsultasi Yoast, Joost de Valk.
Apa yang Google lakukan terbukti tidak efektif ketika berita hoaks tetap menyebar tidak lama setelah terjadi penembakan di Parkland, Florida. New York Times melaporkan, ribuan post dan video muncul di YouTube dan Facebook yang berisi klaim salah bahwa orang-orang yang selamat dari penembakan mematikan itu merupakan aktor bayaran. Selain itu, juga muncul berbagai teori konspirasi lainnya.
Baik Facebook, Twitter, Google maupun YouTube mendapatkan kritik keras karena platform mereka dianggap bisa digunakan untuk menyebarkan propaganda pihak ketiga. Facebook dan YouTube menyebutkan bahwa mereka akan mengembangkan sistem kecerdasan buatan untuk membantu mereka mengidentifikasi dan menghapus konten yang ilegal. Sayangnya, teknologi tersebut masih jauh dari sempurna.
Keduanya juga mengatakan akan mempekerjakan orang-orang sebagai moderator untuk memeriksa konten yang diunggah ke platform mereka. Facebook mempekerjakan 1.000 moderator baru untuk meninjau konten di jejaring sosialnya. Sementara YouTube berencana untuk mempekerjakan total 10 ribu moderator pada akhir tahun ini.Meskipun tidak selamanya berhasil, terlihat jelas bahwa perusahaan-perusahaan teknologi terus berusaha untuk memperbaiki platform mereka, memastikan bahwa informasi palsu dan kebohongan tidak mudah menyebar.
Memang, perubahan yang mereka lakukan bisa memberikan dampak buruk pada bisnis yang menggantungkan diri pada media sosial. Namun, perubahan itu juga berarti bahwa penyebaran konten hoaks juga akan lebih sulit dilakukan.
Tugas pemerintah kita
Selain penindakan oleh polisi, penyebaran hoaks bisa diminimalisir dengan edukasi. Masyarakat Telematika Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menganggap, salah satu alasan hoaks begitu cepat menyebar adalah karena rendahnya tingkat literasi internet masyarakat.
Karena itu, keduanya bekerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia untuk membuat masyarakat semakin mengerti soal penggunaan internet. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika semestinya berada di garda terdepan untuk menggalakkan literasi digital secara berkesinambungan, bukan semata-mata program singkat dan dadakan.
Di luar itu, kita sebagai pengguna media sosial, mestinya bersikap lebih kritis terhadap segala informasi yang beredar karena, mengutip ucapan Mr.Robot, media sosial adalah "Controlled isolated bubbles".